Preskripsi dan Deskripsi dalam Kajian Hukum: Saripati Diskusi Disertasi (part 2) (Serial pertama T-Talk, ISLaMS)
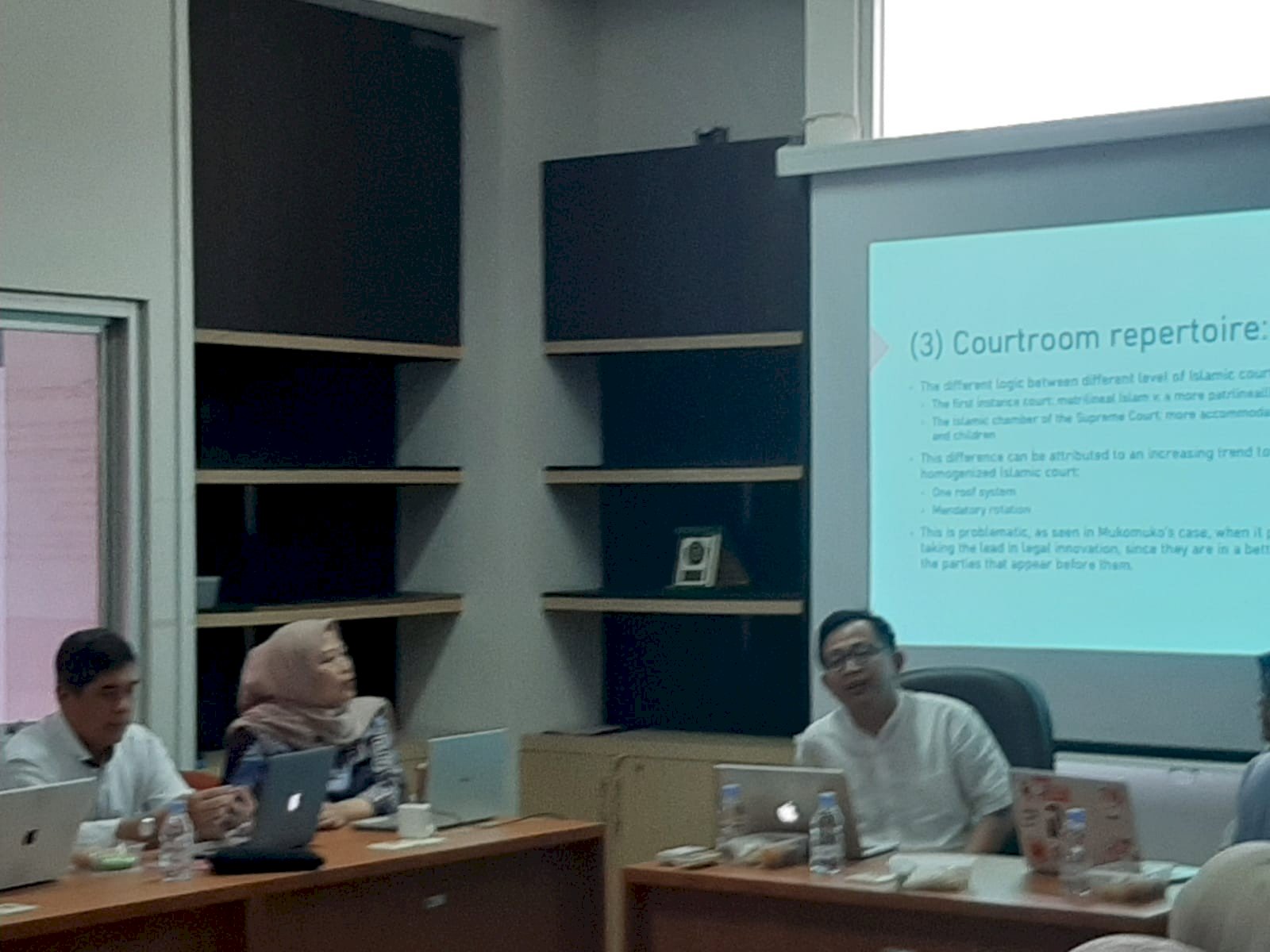
oleh Euis Nurlaelawati
Lalu bagaimana hukum dikaji dengan kacamata ilmu sosial? Dalam kajian hukum, kita bisa meminjam kacamata ilmu sosial. Kajian seperti ini dikenal dengan socio-legal research, yang dikembangkan oleh para pengkaji hukum luar, seperti Eropa (Leiden, VVI) dan Indonesia, seperti UIN dan UGM. Tataran hukum apa yang bisa dikaji? Dua tataran, yaitu teks dan praktik hukum, bisa dikaji dengan pendekatan ini. How? Saya akan paparkan terlebih dahulu pendekatan ilmu sosial dalam kajian praktik hukum, dimana praktiik hukum didekati dengan kacamata ilmu sosial dimana sosial di sini mengacu pada sosiologi, antropologi, psikolgi, politik, dan ilmu sosial lainnya. Untuk kajian ini, biasanya kita menemukan gap, dan gap menurut saya bisa ditemukan antara praktik hukum dengan norma hukum, dan pertanyaannya bisa menggunakan kata tanya, bagaimana, mengapa, dan juga secara lebih spesifik sejauhmana dan lainnya.
Terkait pendekatan ini, memang terdapat perdebatan. Beberapa ahli atau akdemisi hukum mengganggp pendekatan ini tidak relevan untuk kajian hukum, beberapa yang lain justru menenmukan relevansi yang sangat tinggi dalam kajian hukum. Kalangan sarjana hukum yang mendukung pendekatan ini berpendapat bahwa penggunaan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dalam mempelajari hukum Islam sangat penting untuk mengembangkan hukum (hukum Islam, dan atau khususnya dalam konteks diskusi kita ini, hukum keluarga Islam). Mereka berpendapat bahwa dengan hanya menggunakan pendekatan normatif penelitian ini menyebabkan hukum menjadi stagnan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum itu sendiri dan tidak menyelesaikan permasalahan implementasi atau praktek nyata hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat Islam. Oleh karena itu, para sarjana dan mahasiswa hukum mulai kembali memantapkan diri mereka untuk menerapkan pendekatan ini. Dengan pendekatan itu mereka, misalnya, bertanya dalam kajian mereka; mengapa umat Islam tetap menikah secara informal dan/atau menikah pada usia muda (di bawah umur), mengabaikan usia minimal menikah yang ditentukan negara? Sejauh mana pencatat perkawinan beradaptasi dengan sikap hukum masyarakat dan bagaimana mereka memposisikan diri sebagai praktisi hukum dalam pemikiran hukum yang majemuk? Bagaimana hakim Muslim mengintegrasikan atau memasukkan nilai-nilai budaya dalam menyelesaikan kasus yang diajukan ke hadapannya? Mengapa masyarakat Mulsim (di sebuah wilayah) menyelesaikan konflik kewarisan (atau konflik properti lainnya) melalui peradilan (padahal misalnya banyak kalangan lain mengandalkan otoritas ulama dan adat)? Apa yang menyebabkan perempuan Muslim mengabaikan hak-hak hukum mereka atas harta mereka setelah perceraian (padahal mereka tahu bahwa itu adalah hak hukum mereka)?
Kajian dengan fokus pertanyaan seperti ini berkontribusi pada pemahaman nilai-nilai masyarakat Muslim dan sistem yang terkandung dalam norma hukum. Mereka juga menginformasikan sikap hukum masyarakat Muslim dan faktor pendorong sikap hukum mereka. Pengetahuan atau temuan praktik hukum tersebut telah menawarkan wacana teoretis, bahwa misalnya praktik hukum keluarga Islam di masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, latar belakang pendidikan dan ekonomi atau kepentingan finansial, dan motif ideologis, serta memberikan landasan empiris. agar pengembangan dan reformasi hukum dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait.
Dengan kajian seperrti ini, kita tidak sedang memberikan resep langsung untuk kesembuhan permasalahan praktik hukum di kalangan masyarakat, tetapi mendeskripsikan dengan mendalam atau elaboratif kualitatif permasalahn tersebut. Dengan deskripsi analitis tersebut, kita mengetahui akar permasalahan dan secara implikatif memberikan kontribusi praktis.
Al Farabi dan Maulidia menlakukan kajian seperti di atas. Mereke tidak mencoba memberikan preskripsi langsung tetapi memaparkan secara mendalam (descriptive atau verstechen) tentang praktik hukum di masyarakat dengan mempertimbnagkan berbagai variable, seperti unsur keyakinan terhadap adat, otoritas agama, sistem kekeluargaan, dan lainnya. Al Farabi misalnya secara gamblang seperti telah dengan jelas disarikan oleh prof Ali Sodiqin, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis; bagaimana masyarakat Muslim Mukomuko menegosiasikan hukum lokal mereka dengan hukum negara, mengapa mereka mempertahankan hukum adat yang cenderung matrilineal dan mencoba menghindari hukum negara yang dianggap terinspirasi banyak oleh hukum Islam, dan sejauhmana negara, pengadilan agama, merespon sikap hukum masyarakat Muslim tersebut. Dengan pemahaman hukum Islam negara yang sangat baik, ia mencoba menggali fakta melalui data-data yang dikumpulkan terkait dua isu hukum keluarga ia anggap sebagai produk otonomi pengadilan, yaitu Isbat nikah dan broken marriage. Dengan tegas, ia mengungkapkan bahwa masyarakat Mukomuko (perempuan dan anak-anak) merasa dirugikan dengan penrrapan hukum Islam ala negara, bahwa sistem kinship tidak relevan dengan mekanisme keadilan lokal Mukomuko (menyadari konsep legal differentiation), dan bahwa para hakim akhirnya mencoba menagkomodir sikap atau upaya shopping hukum masyarakat di pengadilan dengan lebih cermat, memeprtimbangkan sangat cermat dan menggali dan memahami kultur masyarakat (cultural expertise). Ia mendeskripsikan dengan gamblang, lugas, jelas dan analitik, menampilkan fakta hukum di masyarakat. Fakta ini dapat diolah oleh para pemangku kebijakan hukum serta para pembuatnya untuk dijadikan bahan pengembangan hukum atau mungkin pengubahan terhadap pola pikir hukum masyarakat dengan menyelesaikan faktor di belakang pola pikir tersebut, yang tentunya perlu melibatkan para pihak yang relevan dengan permasalahan yang ada.
Maulidia dengan cermat melihat bagaimana masyarakat Syiah pengungsi melakukan upaya negosiasi terhadap sikap masyarakat Muslim atas keberadaan mereka, terutama kaitannya dengan upaya dalam pengambilan hak-hak adminstrasi keluarga mereka. Ia juga menggali sikap pemerintah dalam menyediakan perlindungan hak-hak administrasi kaum syiah pengungsi, strategi yang dimainkan pemerintah untuk mengakomodir kedua kelompok, yaitu Syiah dan masyarakat tempat kaum Syiah mengungsi dan menetap. Maulida menemukan bahwa kaum Syiah pengungsi mencoba memahami dan mematuhi sikap pemerintah (penghulu dan pihak yang relevan) dalam memberikan hak-hak administrasi mereka yang berbeda dengan pelayanan penghulu terhadap kaum non-syiah. Maulida menyimpulkan bahwa merasa bahwa mereka minoritas dan memperoleh resistensi dari masyarakat, kaum Syiah mencoba berdamai dengan keadaan dan dengan sikap pemerintah dan masyarakat.
Pendekatan socio-legal dalam pemahamanan saya bisa juga digunakan dalam mengkaji teks (norma) hukum. Hukum keluarga Islam yang dierkenalkan oleh negara dapat dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang dan setting sosial dimana hukum tersebut diperkenalkan atau disusun. Setting sosial yang membawa ketentuan sebuah isu hukum tertentu, seperti usia minimum pernikahan dan pernikahan beda agama, bisa dieksplor dan disuguhkan melalui kajian ini. Teori bahwa hukum merupakan refleksi dari tindakan dan keadaan masyarakat menjadi relevan dengan arah kajian ini. Ilmu sosial spserti sejarah dan politik bisa diandalkan dalam kajian ini; variable atau unsur fakta masyarakat, waktu, tempat, pihak penguasa (aktor), dan lainnya yang relevan dengan hal-hal yang melingkupi ilmu sejarah dan polittik dapat diungkap untuk memahami mengapa ketentuan hukum secara tekstual disediakan demikian. Ini untuk bisa kemudian kita mengkritisi juga sejauhmana ketentuan hukum tersebut masih atau tidak lagi relevan dengan konteks sekarang. Kajian terhadap teks hukum dengan demikian juga akan bermanfaat sama dengan kajian terhadap praktik hukum dalam pendekatan ilmu sosial terhadap pengembangan hukum sebagai kontribusi praktis dari kajian-kajian dengan kacamata ini (Euis Nurlaelawati).
.png)
.png)
.png)
